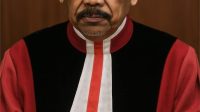Oleh Taufiq Fredrik Pasiak *)
Semarak.co – Beberapa waktu lalu, kami dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta mendapat kehormatan bersilaturahmi dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) H. Wihaji.
Dalam diskusi hangat yang tak hanya strategis tapi juga reflektif, kami membicarakan bentuk-bentuk kolaborasi antara kampus dan birokrasi untuk memperkuat fondasi bangsa: keluarga. Di tengah percakapan, Pak Menteri menyampaikan satu hal yang menggugah sekaligus menggelisahkan—tentang maraknya fenomena keluarga baru.
Sebuah istilah yang mengacu pada rumah tangga yang diisi dua orang dewasa dan satu benda bercahaya: handphone atau ponsel (telepon selular). Dalam keluarga baru ini, gawai alias handphone lebih dulu disambut daripada anak yang pulang sekolah.
Notifikasi lebih cepat direspons ketimbang tangisan bayi. Pelukan tergantikan oleh emoji, dan suara batin anak perlahan diredam oleh suara video pendek yang tak berhenti. Rumah menjadi tempat tinggal, bukan lagi tempat pulang.
Dan itulah awal keretakan bangsa—bukan karena perang, tapi karena tak ada lagi pelukan dan kelekatan. Keluarga baru” itu tampak modern, tapi sebenarnya kehilangan fungsi paling purba: kelekatan. Ia penuh cahaya biru dari layar, tapi minim cahaya batin.
Di dalamnya, anak belajar bahwa perhatian harus diperjuangkan, bukan diberikan. Mereka belajar bahwa cinta adalah soal delay dan scroll, bukan soal hadir dan mendengar. Ayahnya sibuk mengutak atik sosmed sembari menyuruh diam.
Ibunya sibuk merekam story sambil lupa menyapa. Dan anak-anak tumbuh sebagai algoritma dari trauma yang tak pernah diberi nama. Mereka bisa menghafal banyak lagu viral, tapi tak hafal bagaimana rasanya dipeluk hangat setelah menangis. Ini bukan keluarga digital.
Ini keluarga yang terdegradasi. Dan yang lebih menakutkan: kita mulai menganggapnya wajar. Kita tersenyum saat anak, bahkan bayi, bisa diam karena diberi layar, tanpa sadar bahwa kita sedang memperkenalkan narkotik pertama berbasis cahaya.
Kita bangga saat anak-anak bisa main sendiri di pojok rumah, tanpa menyadari bahwa mereka sedang belajar menjadi manusia yang tak tahu cara meminta bantuan. Kita sibuk memberi gadget terbaik, tapi lupa memberi yang paling mendasar: kehadiran.
Kita menyebutnya kemajuan, tapi lupa bertanya: kemajuan ke mana? Kita membangun jalan tol antar kota, tapi gagal membangun jalan pulang antarhati dalam satu rumah. Kita bangga dengan jumlah pasukan dan panjang jembatan, tapi tak pernah menghitung berapa banyak anak yang kehilangan arah karena tidak pernah disentuh dengan cinta.
Kekuatan bangsa tidak ditentukan oleh daya ledak senjata, tapi oleh daya lekat pelukan. Seorang anak yang tumbuh tanpa kehangatan, tanpa validasi, tanpa hadirnya figur dewasa yang bisa ditatap matanya—akan tumbuh membawa lubang.
Dan lubang itu suatu hari akan mencari cara untuk diisi: dengan kekuasaan yang menindas, narkoba yang membius, ideologi yang radikal, atau kekerasan yang membungkam rasa sakit. Bangsa tidak runtuh karena perang besar. Ia rapuh karena kehilangan kelekatan kecil yang tak pernah dianggap penting.
* Riset Neurosains
Riset-riset neurosains saat ini memberikan bukti bahwa pelukan bukan hanya ekspresi kasih, tapi kebutuhan biologis. Kehangatan fisik dari pelukan, tatapan mata yang tulus, dan suara lembut yang menenangkan, semuanya memicu pelepasan oksitosin, hormon keterikatan yang memperkuat rasa aman dan menurunkan kadar kortisol—hormon stres yang merusak jika berlebihan di masa tumbuh kembang.
Ruth Feldman (DOI: 10.1016/j.tics.2016.11.007) dalam telaah pentingnya tentang neurobiologi kelekatan manusia menegaskan bahwa pelukan dan interaksi penuh kasih antara ibu dan anak memicu biobehavioral synchrony yakni penyelarasan antara respons tubuh dan sistem saraf dua manusia yang saling terikat.
Proses ini melibatkan kerja silang antara oksitosin dan dopamin di wilayah otak seperti striatum dan prefrontal cortex, menciptakan jaringan sosial dalam otak yang menjadi fondasi empati, kontrol emosi, dan kemampuan mencintai.
Feldman menyebutnya sebagai “neural choreography of love”—tarian biologis yang terjadi saat ibu dan anak saling hadir dan terhubung. Namun dalam “keluarga baru” hari ini, neural choreography of love itu terganggu oleh satu anggota rumah yang tak pernah tidur: gadget.
Ia hadir setiap waktu—di meja makan, di ruang tidur, bahkan saat tangan orangtua seharusnya menggenggam tangan anak. Di hadapan layar yang menyala, sinkronisasi biologis antara ibu dan anak terputus.
Yang terbentuk bukan lagi biobehavioral synchrony, tapi neurobehavioral asynchrony—ketika tubuh berada bersama, tetapi jiwa dan atensi tercerai. Anak menangis, ibu mengangguk ke layar. Anak ingin bicara, ayah justru menjawab chat.
Teknologi tidak lagi menjadi alat bantu, tapi mengambil alih fungsi keterikatan. Penelitian terbaru dari Radesky et al. (2020) menunjukkan bahwa paparan konstan gadget dalam keluarga berkontribusi pada meningkatnya gangguan regulasi emosi, kecanduan dopamin digital, dan melemahnya ikatan afektif antara orangtua dan anak.
Anak dibesarkan oleh notifikasi, bukan oleh sentuhan. Mereka belajar bahwa kehadiran bukan soal tatap mata, tapi soal sinyal WiFi. Mereka tahu cara membuka iPad, tapi tak tahu cara membuka percakapan.
* Smartphone Bukan Musuh, Tapi Cermin
Pak Menteri Wihaji, demikian juga saya, tentu tidak sedang mengutuk teknologi. Saya juga tidak romantik dengan masa lalu. Kita hidup di zaman yang memang menuntut konektivitas digital. Smartphone bukan musuh—tapi cermin.
Ia merefleksikan cara kita memilih hadir atau abai, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Teknologi tidak membahayakan kelekatan—yang membahayakan adalah ketidaksadaran kita saat teknologi mengambil alih peran kelekatan itu sendiri.
Saya kutipkan satu studi terbaru dari Ajiore Kolade dkk. (2023): “Smartphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern dan dapat digunakan secara produktif dalam interaksi orangtua dan anak—dengan catatan bahwa orangtua memberikan contoh yang baik untuk ditiru anak, mengakses informasi yang sesuai, serta menunjukkan sikap dan pendekatan yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak.”
Pandangan berbasis riset ini patut diapresiasi. Artinya, teknologi tak harus dijauhi, tapi harus dijinakkan. Smartphone bisa menjadi jembatan empati—asal orangtua tetap hadir secara psikologis, bukan sekadar log in secara digital.
Gadget bisa mempererat, bukan memisah—asal kita tidak menyerahkan sepenuhnya waktu anak pada mesin yang tidak pernah memeluk. Yang kami kritik bukanlah kemajuan, tapi ketergelinciran kita yang menyamakan “terhubung” dengan “terkoneksi.”
Kita bangga karena bisa video call setiap saat, padahal kita gagal membaca emosi anak di ruang yang sama. Kita menyebut diri sebagai keluarga modern, padahal kita bahkan tak ingat kapan terakhir kali makan malam tanpa layar.
Kita tak bisa mundur dari dunia digital—dan memang tidak perlu. Tapi kita juga tak bisa terus maju tanpa arah, membiarkan gadget mengambil alih ruang paling sakral dalam keluarga: kehadiran. Smartphone bukan musuh, tapi tantangan moral.
Ia menuntut kita untuk bijak, bukan panik. Karena yang dibutuhkan hari ini bukan pelarangan, tapi keteladanan. Kita tak butuh keluarga yang bebas gawai, tapi keluarga yang tidak meletakkan gawai di atas cinta.
Satu pelukan yang sungguh hadir tetap lebih ampuh daripada seribu emoji. Satu tatapan yang penuh perhatian dapat menenangkan sistem saraf anak lebih dalam daripada animasi paling indah sekalipun.
Maka barangkali, pembangunan terbaik yang bisa kita mulai bukan sekadar jalan tol antar kota, melainkan jalan pulang antar hati—dimulai dari rumah.
Bukan dengan proyek beton, tapi dengan proyek kelekatan. Bukan dari kecanggihan, tapi dari cinta yang dilatih tiap hari: dalam kehadiran, dalam pelukan, dalam mendengar. (200625)
*) Ilmuwan Otak, Dekan FK UPN Veteran Jakarta
#Tentang Penulis:
Taufiq Pasiak, seorang dokter, ilmuwan otak. Menekuni bidang Neurosains dengan perhatian khusus pada upaya meningkatkan kemampuan otak, baik untuk kesehatan, pendidikan maupun manajemen SDM. Bekerja sebagai dosen dan peneliti di bidang otak dengan fokus pada upaya memaksimalkan fungsi otak
Sumber: WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN (postSabtu21/6/2025/hms)